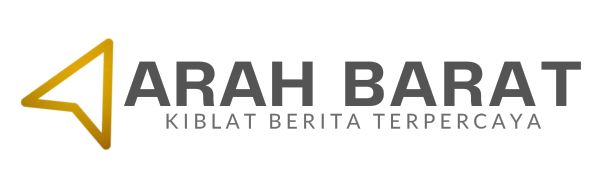Di bawah langit jingga, taman distrik Menore menjadi panggung bagi tubuh-tubuh yang berlari, tawa yang terpantul, dan napas yang mengejar waktu. Di tengah semua itu, seorang pria bernama Arga berdiri, kekar, gagah, memahat dirinya sendiri menjadi sosok yang penuh kebanggaan. Ia berlari dengan dada terbuka, memamerkan otot yang menceritakan kerja keras dan kemenangan atas dirinya sendiri.
Namun, sore-sore itu selalu diiringi oleh kehadiran seseorang. Di sudut taman, di sebuah bangku tua yang terlindung bayangan pohon besar, duduk seorang perempuan berkacamata hitam. Diam. Tak pernah bergerak lebih dari sekadar menghadap ke arahnya.
Arga merasa perempuan itu adalah penonton setianya. Setiap sorot tatapan kosong itu, baginya, adalah pujian tak terucap. Ia berlari lebih cepat, memantulkan bola lebih keras, seolah-olah setiap gerakan adalah persembahan.
Hingga senja ketujuh tiba.
Bangku itu kosong.
*****
Arga, yang biasanya menjadi pusat panggung, kini hanyalah penonton bagi kehampaan. Tidak ada perempuan itu. Tidak ada kehadiran yang membuatnya merasa berarti. Ia menunggu hingga malam menutup taman, namun bangku itu tetap sunyi.
Hari-hari berlalu, dan kehampaan di bangku itu mulai meresap ke dalam dirinya. Penasaran dan gelisah, Arga akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Ia bertanya pada penjaga taman, pedagang kecil, bahkan orang-orang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Hingga sebuah petunjuk membawanya ke balik taman, ke sebuah gang kecil yang tersembunyi di balik waktu.
Gang itu sunyi, gelap, seperti lorong menuju sesuatu yang terlupakan. Ia mengikuti petunjuk langkah demi langkah, hingga tiba di depan sebuah rumah kecil. Di sana, bendera kuning berkibar perlahan, ditiup angin senja yang kian redup.
Arga merasa dadanya sesak. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, dan seorang wanita tua membukanya.
“Maaf,” kata Arga pelan, suaranya nyaris hilang. “Saya mencari seorang perempuan muda yang sering duduk di taman… berkacamata hitam.”
Wanita itu tersenyum pahit, lalu mengangguk. “Itu anak saya, Nira. Dia sudah pergi.”
“Pergi?” ulang Arga, suaranya tercekik.
Wanita itu mengangguk lagi. “Dia meninggal tujuh hari lalu. Serangan jantung.”
Tujuh hari. Tepat hari pertama bangku itu kosong.
*****
Arga mencoba menenangkan dirinya. “Dia… selalu duduk di bangku taman. Dia… melihat saya, bukan?”
Wanita itu tertawa kecil, tapi bukan tawa yang bahagia. “Nira buta sejak lahir. Dia tidak pernah melihat apa pun, termasuk kau, Nak.”
Arga membeku. Dunia seolah runtuh di sekitarnya. Semua gerakan, semua pameran, semua egonya… ternyata tak pernah dilihat.
“Tapi dia sering bercerita,” lanjut wanita itu. “Tentang suara yang ia dengar di taman. Suara langkah kaki penuh semangat, pantulan bola yang ritmis, suara seseorang yang tak ia kenal tapi ia kagumi. Katanya, itu suara kehidupan.”
Arga terdiam. Perempuan itu tidak pernah melihat otot-ototnya, tidak pernah tahu wajahnya. Yang ia dengar hanyalah suara yang melintas, yang mungkin tak pernah ia niatkan untuk membuat kesan.
“Tapi kenapa… dia selalu ada di sana, seperti memperhatikan?” tanya Arga.
Wanita itu tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. “Karena dia mendengar dunia lebih indah dari kita yang melihatnya. Dan mungkin, tanpa kau sadari, dia telah menemukan kehidupan dalam suara langkahmu.”
Arga meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang tak terdefinisi. Semua kebanggaan, semua keyakinan, berubah menjadi abu. Namun, di antara serpihan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh.
*****
Malam itu, ia kembali ke taman. Duduk di bangku tempat Nira biasa berada, ia menutup matanya. Ia mencoba mendengar seperti Nira.
Ada suara daun yang berbisik lembut di angin, suara langkah-langkah yang tergesa, suara bola yang memantul jauh, dan suara tawa anak-anak. Perlahan, ia menyadari bahwa dunia ini lebih besar dari dirinya. Lebih indah dari sekadar tubuh yang ia banggakan.
Esoknya, Arga menempatkan sebuah papan kecil di bangku itu. Di sana tertulis:
“Untuk Nira, yang melihat dunia dengan telinga dan merasakan kehidupan dengan hati. Terima kasih telah mengingatkan, bahwa yang indah tak selalu terlihat, dan yang penting tak selalu tampak.”
Di bawah senja yang sama, taman itu tetap penuh kehidupan. Tapi Arga tahu, sebagian dari kehidupannya kini adalah pelajaran yang ia temukan dari seorang perempuan buta yang tak pernah melihatnya.***Ngabehi FH