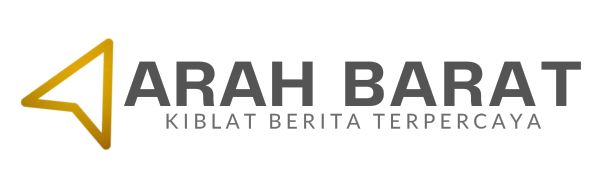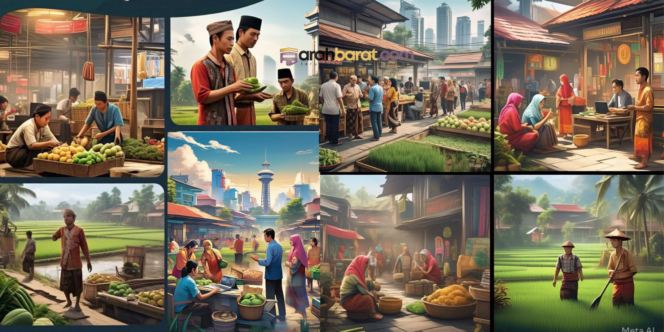Lampung, tanah kaya budaya dan potensi alam yang melimpah, menyimpan mimpi besar untuk maju, terlebih di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur muda, Mirza-Jihan. Namun, penting menjadi catatan bahwa pembangunan berkelanjutan tak sekadar membangun infrastruktur dan menggenjot ekonomi. Lebih dari itu, ia harus memberdayakan masyarakatnya, menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek pembangunan.
Tulisan ini salah satunya adalah ikhtiar urun rembuk, menawarkan gerakan kebudayaan sebagai jaalan untuk memberdayakan masyarakat. Kunci utamanya? Gerakan kebudayaan—strategi yang tak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mentransformasi cara berpikir, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat agar mampu berdiri di kaki sendiri. Ini selaras dengan konsep pemberdayaan yang menekankan kemandirian dan swadaya, seperti yang ditekankan oleh Amartya Sen dalam karyanya, Development as Freedom (1999), yang menekankan pentingnya kemampuan dan kesempatan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Konsep ini juga dielaborasi oleh Martha Nussbaum dalam Creating Capabilities: The Human Development Approach (2011), yang menjabarkan dimensi-dimensi kemampuan manusia yang perlu dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan sejati.
Bayangkan sebuah Lampung yang masyarakatnya tak hanya menerima bantuan, tetapi juga aktif menciptakan solusi bagi permasalahan mereka sendiri. Gerakan kebudayaan inilah yang menawarkan jalan menuju visi tersebut. Ia berakar pada beberapa prinsip fundamental. Pertama, kesadaran kolektif. Masyarakat harus menyadari potensi dan tantangan yang dihadapi, lalu berperan aktif mencari solusinya. Ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire tentang pendidikan kritis, yang menekankan pentingnya kesadaran diri dan kemampuan untuk menganalisis realitas sosial (Freire, 1970). Bukan sekadar pemberian informasi, melainkan proses pemahaman diri dan lingkungan yang mendalam. Benedict Anderson, dalam Imagined Communities (1983), menunjukkan bagaimana kesadaran kolektif dibentuk melalui narasi dan identitas bersama.
Kedua, partisipasi aktif. Setiap individu, dari keluarga hingga organisasi masyarakat, memiliki peran penting yang harus dihargai dan difasilitasi. Margaret Mead, dalam berbagai tulisannya, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Mead, 1935).
Ketiga, kemandirian dan swadaya. Pemberdayaan bukan sekadar memberi ikan, tetapi mengajarkan cara memancing—mengembangkan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk berkembang mandiri dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran pembangunan manusia (human development) yang dipelopori oleh UNDP, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas manusia (UNDP, 2023).
Keempat, keberlanjutan. Perubahan yang dihasilkan harus berdampak jangka panjang, bukan solusi sementara. E.F. Schumacher, dalam Small is Beautiful (1973), mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan pembangunan.
Gerakan Kebudayaan Lokal; Sebuah Perspektif
Narasi pemberdayaan di Lampung tidak boleh dilepaskan dari filosofi dan kearifan lokalnya. Konsep piil pesinggi (memegang teguh kehormatan dengan saling menghormati), nemui nyimah (saling mengunjungi dan mempererat silaturahmi), sakai sambayan (gotong royong dan kebersamaan), dan nengah nyeppur (berusaha keras dan pantang menyerah) merupakan pondasi kuat yang dapat diintegrasikan dalam gerakan kebudayaan ini.
Piil pesinggi, misalnya, dapat diwujudkan melalui program-program yang mendorong dialog antar-kelompok masyarakat, menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun rasa saling percaya. Sementara nemui nyimah dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat ikatan sosial, menciptakan rasa kebersamaan seperti yang dibahas oleh Emile Durkheim dalam The Division of Labor in Society (1893). Sakai sambayan menjadi landasan bagi kerja sama dalam berbagai proyek pemberdayaan, seperti pembangunan infrastruktur desa atau pengembangan usaha bersama. Semangat nengah nyeppur akan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi, mencerminkan semangat ketahanan dan adaptasi seperti yang dikaji oleh Jared Diamond dalam Guns, Germs, and Steel (1997).
Bagaimana gerakan kebudayaan ini diwujudkan di Lampung? Pertama, melalui pendidikan dan pelatihan yang berakar pada kearifan lokal. Program pendidikan non-formal yang menekankan keterampilan praktis dan literasi, dipadukan dengan nilai-nilai piil pesinggi, nemui nyimah, dan nengah nyeppur, mampu mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Bayangkan pelatihan keterampilan kerajinan tangan tradisional, misalnya; ia tak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga melestarikan warisan budaya.
Kedua, melalui penguatan kelembagaan masyarakat. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat sipil dan koperasi sangat penting sebagai wadah berorganisasi, berkolaborasi, dan mencari solusi atas permasalahan lokal. Koperasi petani, misalnya, dapat meningkatkan pendapatan anggotanya melalui pengolahan hasil pertanian secara bersama-sama dan efisien, mencerminkan semangat sakai sambayan.
Ketiga, melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal. Lampung memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang dapat diolah menjadi produk unggulan, seperti olahan makanan tradisional atau kerajinan tangan, meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ini sejalan dengan semangat nengah nyeppur untuk meningkatkan kesejahteraan.
Gerakan ini berpotensi besar menciptakan dampak positif: peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, jaringan sosial yang kuat, dan inisiatif lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada. Dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten sangat krusial. Perubahan pola pikir masyarakat yang masih bergantung pada bantuan eksternal juga perlu diatasi. Terakhir, kesenjangan akses teknologi dan informasi dapat menghambat proses pemberdayaan.
Di sisi ini pemerintah wajib hadir, lewat regulasi yang berpihak, dukungan stimulus anggaran dan pendampingan pemberdayaan.
Simpulannya, gerakan kebudayaan menawarkan jalan menuju pemberdayaan masyarakat Lampung yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Integrasi teknologi, dukungan kebijakan yang progresif, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama.
Tabik.