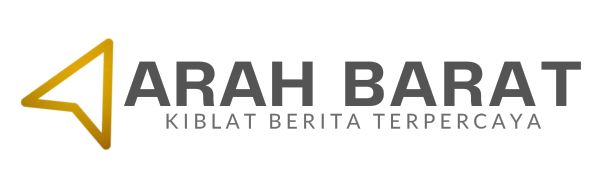Hari itu, rasa sakit datang lagi. Rasanya seperti nonton sinetron kesukaan, lalu listrik mati pas adegan puncak. Elanai Ras menangis sejadi-jadinya, suaranya menggelegar sampai burung-burung di pohon depan rumah sakit mungkin ikut stress. Gadis kecil itu sudah hampir dua minggu menjadi penghuni tetap Rumah Sakit Abdul Moeloek, lengkap dengan kasur tipis yang selalu bunyi kriet-kriet kalau digeser.
Neneknya, pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu sigap, segera keluar memanggil tim medis. Tidak lama kemudian, seorang pria berbaju putih muncul. Lehernya menggantung alat yang oleh Lanai dianggap mirip “mainan bapak-bapak serius.” Itu sebenarnya stetoskop, tapi bagi Lanai, ia lebih mirip mikrofon ala penyanyi dangdut.
“Lanai, biar sakitnya hilang, dokter mau suntik ya. Nggak sakit kok, seperti digigit semut,” kata nenek lembut. Dokter Didi, pria yang jelas-jelas bukan penyanyi dangdut tadi, hanya senyum kecil, mungkin sudah terlalu hafal drama anak kecil di rumah sakit.
Lanai melirik neneknya. Matanya berbicara: “Nenek, jangan biarkan ini terjadi.” Tapi neneknya malah balas menatap penuh kasih, seolah berkata: “Nak, ini demi kebaikanmu. Lagian digigit semut kan nggak bikin mati.
”Dokter Didi mulai membuka suntikan. Dengan kecepatan tangan level master, ia mengisi obat dan cus! Suntikan itu masuk melalui selang infus di tangan Lanai.
“Aduuuhhh!” Lanai menjerit seperti dikejar anjing tetangga. Tapi setelah lima menit, ia sudah tertidur pulas, membuktikan bahwa anak kecil memang ahli dalam urusan drama queen.
Sementara Lanai tidur, percakapan serius terjadi antara dokter dan neneknya. “Ginjal Lanai mengalami kelainan bawaan, Bu,” kata dokter Didi dengan nada seperti pembawa acara TV. “Kami akan terus berusaha. Mohon keluarga tetap berdoa.”
“Iya, Dok. Kami sekeluarga hanya bisa pasrah,” jawab nenek, sambil menghela napas panjang, meski wajahnya tetap terlihat seperti orang yang tidak pernah menyerah.
Ginjal, Desa, dan Kehidupan Tanpa Garam
Lanai didiagnosis menderita uropati kongenital, kelainan ginjal bawaan. Awalnya, ia hanya tidak bisa buang air kecil. Ayah dan ibunya membawa Lanai ke mantri di desa mereka, Sungai Cambai. Mantri bilang, “Santai saja, ini cuma sedikit mampet.” Tapi setelah dirujuk ke rumah sakit, ternyata penyakit itu lebih serius daripada antrean panjang di loket bus.
Setelah hampir sebulan opname, Lanai diperbolehkan rawat jalan. Tapi ada syarat berat: ia harus kontrol seminggu sekali, periksa darah sebulan sekali, dan pantang garam.“
Jadi aku ini seperti kerupuk diet,” pikir Lanai, sambil memandangi sepiring nasi putih dan sayur rebus tanpa rasa.
Makanannya serba direbus. Kalau ada minyak, langsung dieliminasi. Gemuk sedikit, tidak boleh. Kurus berlebih, juga tidak boleh. Hidup Lanai seperti lomba tarik tambang yang nggak ada hadiahnya.
“Kalau begini terus, aku mau jadi anak cosplay aja. Bisa bebas makan nasi goreng,” gumamnya dalam hati sambil mendesah.
Karena pengobatan Lanai butuh biaya besar, ayahnya menjual kebun dan pindah ke rumah kecil di Perumnas Way Halim. Tidak hanya itu, ia juga harus pindah sekolah. Hebatnya, meski umurnya baru delapan tahun, ia langsung masuk kelas tiga setelah tes sederhana. “Hebat juga aku, ya,” pikir Lanai. “Bahkan Einstein mungkin kalah sama proses ini.”
Keluarga yang Tidak Pernah Lelah Berjuang
Biaya pengobatan Lanai luar biasa besar. Ayahnya bekerja keras, mulai dari berkebun, produksi ikan asin dan salai, sampai penggergajian kayu. Semua hasilnya langsung dialokasikan untuk pengobatan Lanai. Keluarga ini tidak punya waktu untuk mengeluh.
Malam itu, sebelum tidur, neneknya berkata lembut, “Lanai, kita ini keluarga pejuang. Kalau kamu kuat, semua ini akan terasa ringan.”
Lanai tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hati ia berbisik, “Nenek, aku akan kuat. Tapi aku minta satu hal, boleh nggak nanti kalau sembuh aku makan kentang goreng pakai garam?” ujar Lanai memelas.
“Hidup tanpa garam itu berat, Nek. Tapi lebih berat lagi kalau aku harus makan sayur rebus sambil senyum.”***