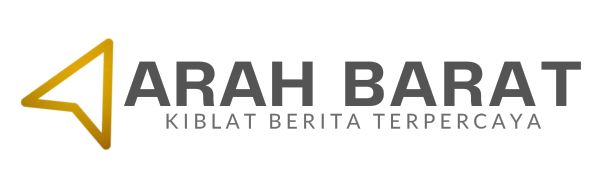Satu tahun di sekolah baru, tahu-tahu sudah waktunya ujian kelulusan. Ini bukan ujian biasa. Ini ujian yang menentukan apakah kami bakal jadi anak SMA keren, atau cuma jadi legenda di warung nasi uduk depan sekolah.
Aku fokus ke EBTANAS. Fokus ini penting, kayak dengar radio sambil cari frekuensi yang pas. Kalau nggak fokus, suara penyiar bisa berubah jadi suara robot. Aku tahu nilai tinggi itu penting buat masa depan. Bayangin aja, kalau aku gagal, pasti Ibu bakal ngomong sambil ngehela napas panjang: “Nak, perjuangan Ibu ini lho… jangan sia-siakan.” Rasanya lebih menusuk daripada soal matematika di ujian.
Jadi, aku habiskan malam-malamku dengan melahap buku pelajaran, sampai nyamuk pun malas mendekat karena pikiranku terlalu serius. Dan hasilnya? Aku lulus dengan nilai kedua tertinggi di sekolah. Lumayan. Peraih nilai tertinggi itu cewek dari kelas B. Pintar banget dia, sampai aku mikir, apa dia lahir sambil baca buku? Tapi, ya sudahlah, nomor dua juga bagus. Yang penting namaku ada di atas nama Andi, teman baikku. Itu cukup bikin aku senyum kecil.
Dengan nilai itu, semua SMA Negeri di Bandar Lampung kayak bilang: “Masuk sini dong!” Tapi ini justru bikin bingung. Pilihan SMA itu kayak menu mie instan, semuanya enak, tapi harus pilih satu.
Dari sinilah aku kemudian punya kesimpulan, “Nilai bagus itu kayak cinta, nggak cukup niat, tapi harus diperjuangkan.
“Aku ingin daftar di SMA favorit. Katanya, sekolah favorit itu keren, fasilitasnya lengkap, pengajarnya berkualitas, dan kantinnya jual gorengan murah. Tapi masalahnya jauh, ongkosnya bikin Ibu harus kerja lebih keras.
“Hidup itu memang penuh pilihan, seperti mie instan. Pilih rasa salah, menyesal semalam.”Sementara itu, Andi datang dengan ide cemerlangnya.
“Daftar aja di sekolah yang sama sama aku. Kita nanti bareng-bareng naik motor. Kamu tinggal duduk manis di belakang, kayak boneka Doraemon,” katanya sambil ngikik.
Sempat tergoda sih. Nebeng motor Andi itu hemat ongkos dan tenaga. Tapi, tiba-tiba wajah Ibu muncul di pikiranku lagi, kayak notifikasi baterai lemah: “Jangan, Nak. Kasihan Ibu.
”Aku cerita ke Andi soal ini. Dia dengar sambil nyengir.
“Yah, kalau SMA favorit, kan pengajarnya lebih bagus,” katanya.
“Iya, tapi kalau aku harus naik angkot setiap hari, ongkosnya mahal. Ibu bisa tambah capek,” jawabku.
“Kan bisa nebeng motor aku.””Terus kalau kita beda jadwal? Kamu pagi, aku siang? Aku naik motor sendiri? Motor siapa yang aku bawa, andalanku kan by sikil. Yang ada aku dikira maling,” kataku lagi.
Andi terdiam. Dia kayak CPU yang kehabisan memori untuk debat. Setelah diskusi panjang dan beberapa bungkus keripik, akhirnya aku putuskan daftar di SMA dekat rumah. Tiga kilometer jaraknya, bisa jalan kaki. Anggap aja olahraga pagi, biar keren sedikit.
Dan akhirnya, aku diterima. Namaku ada di urutan kedua di papan pengumuman. Lagi-lagi nomor satu dipegang cewek. Aku curiga ini semacam konspirasi nasional untuk bikin cowok terlihat biasa-biasa saja. Tapi tetap, melihat namaku di sana, rasanya bahagia banget. Kalau kebahagiaan ini bisa ditukar dengan donat, mungkin aku bisa buka warung sendiri.
“Bahagia itu sederhana, seperti melihat nama kita di papan pengumuman. Apalagi kalau nggak ada tulisan: remedial.”***bersambung