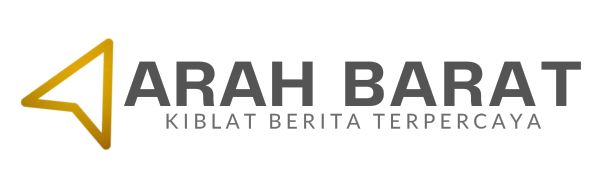Elanai Ras: Si Senyum Malu
Namanya Elanai Ras. Aneh, bukan? Kalau saja nama itu muncul di ujian TTS, aku pasti langsung skip ke pertanyaan berikutnya. Tapi ya begitulah, si pemilik senyum malu-malu itu. Tingginya sedang-sedang saja, kulitnya kuning langsat, rambutnya ikal mayang. Kalau sekali lihat, dia biasa saja—seperti anak remaja lain yang suka lari-lari kecil kalau hujan tiba-tiba turun di sekolah. Tapi kalau kamu berani diam dan pandang dia agak lama, ah, ada sesuatu. Semacam cahaya, binar kecantikan, yang belum jadi tapi sudah bikin orang penasaran.
Hari itu adalah hari pertama aku masuk kelas dua SMP. Dan mereka—anak-anak putih merah—baru saja naik pangkat jadi junior kami. Aku lihat Elanai di antara rombongan mereka, berjalan pelan seperti kucing baru pindah rumah. Matanya celingak-celinguk, dan tiba-tiba—DEG!—mataku bertabrakan dengan matanya.
“Kak, kelas 1.A di mana ya?” katanya pelan, seperti sedang bertanya ke pohon asem.
Aku sempat bengong sebentar. “Oh iya, di sana,” jawabku dengan suara yang—jujur saja—agak goyang. Takutnya dia bingung, aku tarik tangannya pelan-pelan menuju kelasnya. Aku yang waktu itu belum kenal istilah “momen romantis,” ternyata sedang menoreh sejarah. Hari itu pertama kalinya aku menggenggam tangan si Senyum Malu.
“Terima kasih, Kak!” katanya sambil senyum. Duh, senyumnya kayak ucapan terima kasih itu pakai bonus.
Tapi bukan itu yang bikin hari itu terus kuingat. Yang bikin adalah rasa hangat di tanganku, sisa genggamannya. Herannya, hangat itu jalan-jalan, dari tangan ke pundak, terus entah bagaimana, mampir di hati. Dan hati ini, duh tanpa izin aku, langsung menyimpannya.
Aku masih dalam keadaan setengah melayang waktu pulang ke kelas. Hasilnya, aku hampir menabrak pot bunga di depan kelas dua. Untungnya, lonceng besi sekolah langsung bunyi. Itu seperti soundtrack film yang menyadarkan aktor utamanya dari lamunan panjang.
Sialnya Kaki Bau
Aku duduk di kelas A. Kelasnya anak-anak pintar dengan nilai rata-rata di atas tujuh koma. Waktu itu aku bangga masuk sini, sampai akhirnya Bu Tiur—guru sejarah dengan suara seperti toa masjid—mempermalukanku di depan kelas.
“Kamu!” jarinya menunjukku, matanya tajam kayak pisau daging. “Siapa namamu?”
“Mahali, Bu,” jawabku sopan.
“Keluar!” katanya.
“Lho? Salah apa saya, Bu?”
“Bau kakimu itu mengganggu satu kelas. Keluar sekarang juga!
”Waduh, langsung semua mata melirik ke bawah. Aku ikut ngendus pelan, dan benar saja—kakiku aromanya mirip terasi panggang kena angin malam.
Aku keluar kelas sambil merutuk. Tapi yang bikin sakit hati adalah Bu Tiur nggak berhenti di situ. Dari dalam kelas, dia terus ngoceh: “Anak-anak, ini contoh siswa yang tidak baik. Jorok. Kakinya saja bau. Jangan tiru dia, ya!”
Dari hari itu, nama baru melekat padaku: Mahali Kakbau. Bahkan Bu Tiur tak pernah lagi memanggilku Mahali. Selalu, “Kakbau! Kerjakan soal nomor tiga!” atau “Kakbau! Jangan ngobrol!”
Tapi, hei, siapa peduli. Karena bagiku, nama sejati yang penting bukan Mahali, Kakbau, atau apa pun. Nama sejati adalah yang kuingat dari hari pertama itu: Elanai Ras, Si Senyum Malu.***